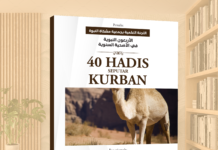عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال : لا ضرر ولا ضرار . حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسنداً وَرَوَاهُ مَالِكٌ في الْمُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضَاً
Dari Abu Sa’īd, Sa’ad bin Mālik bin Sinān al-Khudri raḍiyallāhu ‘anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Tidak boleh melakukan ḍarar dan ḍirār.” Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Dāruquṭnī dan lain-lain dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Mālik dalam al- Muwaṭṭa’ dari Amr bin Yaḥyā dari ayahnya dari Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam secara mursal karena tidak menyebutkan Abu Sa’īd. Hadis ini memiliki beberapa jalur yang saling menguatkan.[1]
Ḍarar dan ḍirar adalah dua kata dalam bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama, yaitu ḍarra (ضر). Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai mudarat. Mudarat sendiri berarti sesuatu yang tidak menguntungkan, kerugian, membahayakan, dan tidak berguna.
Para ulama berbeda pendapat terkait makna ḍarar dan ḍirar sebagai berikut:
- Ḍarar dan ḍirār bermakna sama, disebutkan hanya untuk penekanan. Maksudnya ialah tidak boleh sama sekali memberi dan mendatangkan mudarat bagi diri dan orang lain.[2]
- Ḍarar berarti mendatangkan mudarat bagi orang lain sedangkan ḍirār berarti membalas mudarat orang lain dengan mudarat tidak sesuai syariat[3].
- Ḍarar berarti mendatangkan mudarat bagi orang lain yang menguntungkan diri sendiri sedangkan ḍirār berarti mendatangkan mudarat bagi orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri.[4]
- Ḍarar berarti tidak sengaja mendatangkan mudarat sedangkan ḍirār bermakna sengaja mendatangkan mudarat. [5]
Terdapat lafaz tambahan sebagai berikut dalam hadis Abu Sa’īd,
مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
“Barang siapa yang memberi mudarat, Allah akan menimpakan mudarat baginya. Barang siapa yang menyusahan, maka Allah akan mennyusahkan dirinya.”
Mendatangkan mudarat baik kepada diri sendiri dan orang lain tidak diperkenankan oleh syariat. Imam Abu Dāwud menjadikan hadis ini sebagai salah satu hadis yang menjadi poros fikih Islam.[6] Olehnya, para ulama menjadikan hadis ini sebagai kaidah fikih, yaitu kaidah:
الضرر يزال
“Mudarat itu dihilangkan.”
Sebagian ulama mempertahankan lafaz hadis sebagai kaidah fikih dan dianggap lebih unggul karena beberapa hal, yaitu:
- Mempertahankan nas dari Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam.
- Menafikan dua macam jenis kemudaratan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa ḍarar dan ḍirār
- Mencakup usaha preventif terhadap mudarat yang akan terjadi dan upaya penanggulangan terhadap mudarat yang telah terjadi.[7]
Mudarat yang dinafikan dalam hadis ini adalah mudarat yang timbul tanpa disyariatkan. Mudarat yang diakomodir oleh syariat tentu dibolehkan, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri barang dengan nilai di atas seperempat dinar, hukum rajam bagi pezina yang berstatus muḥṣan, hukum dera bagi orang yang menuduh orang lain berzina, menjual paksa harta orang yang enggan membayar hutangnya, dan lain sebagainya. Tentunya, penetapan hukum-hukum tersebut dilakukan oleh pemerintahan kaum muslimin, bukan individu atau kelompok.
Dalam ibadah vertikal pun, mudarat ini dinafikan oleh syariat. Misalnya, orang sakit yang ingin melaksankan salat tentunya harus bersuci dengan cara berwudu. Namun demikian, berwudu dapat menambah penyakit orang tersebut atau memperlambat penyembuhannya. Tentu ini adalah mudarat, harus dihindari. Oleh karena itu, ia diperkenankan untuk bertayamum guna menghindari mudarat tersebut. Demikian pula orang yang tidak mampu berdiri untuk mengerjakan salat wajib. Apabila ia berdiri, dikhawatirkan akan ada mudarat yang menimpa dirinya. Olehnya, ia diperkenankan mengerjakan salat wajib tersebut sambil duduk dan seterusnya. Para ulama merumuskan sebuah kaidah lain terkait ini, yaitu:
المشقة تجلب التيسير
“Kesulitan itu mengundang kemudahan.”
Para ulama berdalil dengan hadis ini terkait beberapa turunan kaidah fikih di atas. Di antaranya:
- Apabila terdapat dua mudarat yang tidak mungkin dihindari salah satunya, diperkenankan mengerjakan yang paling ringan mudaratnya. Misalnya, jika ada orang yang jika salat wajib dalam keadaan berdiri, auratnya tersingkap. Jika salat dalam keadaan duduk, auratnya tertutupi. Dalam keadaan seperti ini, ia diperkenankan salat dalam keadaan duduk meski ia mampu berdiri.
- Jika terdapat dua perkara haram, yang paling ringan keharamannya didahulukan. Contohnya, jika ada orang yang dipaksa minum sesendok sianida (zat beracun) atau minum sesendok minuman keras, hendaknya ia memilih yang paling ringan mudaratnya.
Wallāhu a’lam.
Footnote:
[1] H.R. Ibnu Majah (2337) dan (2339), al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubrā (11497-11499) dan (11980), al-Dāruquṭnī (4540), Ahmad (2129),(2344),(2801) dari Ibnu ‘Abbās bukan dari Abu Sa’īd al-Khudri. Hadis Abu Sa’īd al-Khudrī diriwayatkan oleh Imam Mālik (2758), al-Ḥākim (2358), al-Baihaqī (11502, 11503, 11996, 20507) dan al-Dāruquṭnī (30709, 4541). Hadis ini memiliki beberapa syawāhid yaitu hadis ‘Ubādah bin al-Ṣāmit, Abu Hurairah, Abu Lubābah, Ṡa’labah bin Abī Mālik, Jābir bin ‘Abdillāh, dan ‘Āisyah (lihat: Naṣb ar-Rāyah, 4/384). Ibnu Ṣalāh berkata, “Kumpulan hadis-hadis tersebut menguatkan hadis ini dan menjadikannya hasan. Mayoritas ulama pun menerima dan berpegang dengan hadis ini.” Hadis ini juga dihasankan oleh Ibnu Rajab (lihat: Silsilah al-Aḥādiṣ al-Ṣaḥīḥah (1/503).
[2] Al-Tamhīd (20/157).
[3] Al-Wāfi hal. 240.
[4] Al-Ḥulal al-Bahiyah hal. 257.
[5] Idem.
[6] Al-Jāmi’ li Akhlāq al-Rāwi wa Ādāb al-Sāmi’ (1886). Ibarat beliau,
الفِقْهُ يَدُورُ عَلى خَمْسَةِ أحادِيثَ: «الحَلالُ بَيِّنٌ والحَرامُ بَيِّنٌ»، وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إنَّما الأعْمالُ بِالنِّيّاتِ وإنَّما لِامْرِئٍ ما نَوى» وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ قالَ: «إنَّما الدِّينُ النَّصِيحَةُ» وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ قالَ: «ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فاجْتَنِبُوهُ وما أمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنهُ ما اسْتَطَعْتُمْ».
[7] Lihat: al-Jawāhir al-Madaniyah hal. 23.