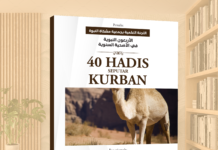Daftar isi:
Redaksi Hadis:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ.
Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, jika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya’.”
Takhrij Hadis:
Hadis ini madar-nya (poros periwayatannya) adalah Ibnu Syihab al-Zuhri. Dari beliaulah jalur periwayatan hadis ini diperselisihkan menjadi beberapa jalur, yaitu:
Jalur pertama, jalur Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwail, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Hadis ini dikeluarkan secara maushul oleh Tirmidzi[1], Ibnu Majah[2], dan Ibnu Hibban.[3]
Dan jalur ini yang menjadi pijakan Ibnu Hajar di dalam Kitabul Jami’.
Namun sanad hadis ini dinilai lemah oleh sebagian para ulama, sebab menurut Ibnu Hajar derajat Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwail jujur namun memiliki hadis-hadis yang mungkar[4]. Al-Dzahabi mengatakan, “Divonis lemah oleh Yahya bin Ma’in.” Imam Ahmad mengatakan, “Hadisnya sangat mungkar[5].
Dengan demikian, sanad hadis di atas adalah lemah disebabkan oleh kelemahan sosok Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwail ini.
Jalur kedua, jalur Abdullah bin ‘Umar al-‘Umary, dari al-Zuhri, dari ‘Ali bin Husain Zainal Abidin, dari ayahnya Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Jalur ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad[6].
Sanad hadis ini juga lemah, karena faktor kelemahan Abdullah bin ‘Umar al-Umary. Ibnu Hajar mengatakan, “Lemah namun ahli Ibadah.”[7]
Sejatinya, kolaborasi antara dua jalur ini bisa mengantarkan hadis ini menjadi hasan lighairihi, seperti yang disebutkan oleh oleh para ulama. Di antaranya Imam Nawawi[8], Ibnu Hajar al-‘Asqalani[9], dan Syekh Syuaib al-Arnauth[10].
Jalur ketiga, jalur Imam Malik, dari Imam al-Zuhri, dari Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Jalur ini dikeluarkan oleh Imam Malik.[11]
Di jalur periwayatan yang ketiga ini, Imam Malik diperkuat oleh Imam-Imam hadis yang lainnya, seperti Ma’mar bin Rasyid al-Azdi[12], Yunus bin Yazid al-Aily[13], dan Ibrahim bin Sa’a. [14] Semuanya (perawi di atas) meriwayatkan dari al-Zuhri, dari Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib secara mursal.
Jadi jalur ini mursal, sebab Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib seorang tabiin, dan beliau tidak menyebutkan nama sahabat dalam riwayat ini, tetapi langsung menyandarkan hadisnya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Kesimpulannya, jalur periwayatan yang ketiga dianggap oleh sebagian ulama hadis –khususnya pakar ‘ilal – sebagai jalur yang terkuat, sebab perawi dari Ibnu Syihab al-Zuhri lebih kuat secara kuantitas dan kualitas.
- Secara kuantitas, perawi jalur ini lebih banyak dari Ibnu Syihab al-Zuhri, yaitu empat orang, sedangkan jalur maushul hanya dua orang.
- Secara kualitas, perawi jalur ini jauh lebih berkualitas, mereka adalah para imam-imam hadis yang sangat populer dan disepakati kompetensinya dalam masalah hadis, seperti Ma’mar bin Rasyid al-Azdi, Imam Malik, dan Yunus bin Yazid al-Aily, bahkan merupakan murid terdekat dari Ibnu Syihab al-Zuhri[15].
Berpijak pada fakta ini, sebagian pakar hadis seperti Imam al-Bukhari[16], al-Tirmidzi[17], al-Daruqudni[18], Yahya bin Ma’in[19] memenangkan jalur periwayatan yang mursal ini.
Ibnu Rajab al-Hanbaly mengatakan, “Hhadis ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dari beberapa jalur yang lain (selain jalur periwayatan di atas), namun semuanya lemah”[20].
Dan hadis mursal merupakan salah satu jenis hadis lemah dalam klasifikasi disiplin ilmu hadis.
Kendati hadis ini lemah dari sisi sanad, namun makna yang dikandung oleh hadis ini benar dan diakomodir oleh syariat, di antaranya oleh hadis Nu’man bin Basyir, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِه
“Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya.”[21]
Profil Sahabat:
Nama Asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr al-Dausi, seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang fokus dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Olehnya, bukan perkara yang mengherankan jika namanya begitu kerap disebutkan ketika seseorang membaca hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaih wasallam. Beliau wafat pada tahun 57 H.
Penjelasan Hadis:
Hadis ini merupakan salah satu representasi jawamiul kalim bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu ucapan yang ringkas, namun mengandung makna yang dalam dan luas[22], sehingga sangat layak untuk didaulat sebagai pilar dalam perkara agama.
Secara spesifik, hadis ini merupakan salah satu pilar dalam perkara adab, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abu Zaid al-Qairawani al-Maliki rahimahullah bahwa pilar-pilar adab ada empat hadis[23], yaitu:
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ –
مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ –
لَا تَغْضَبْ –
لا يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِه –
– Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ
“Di antara tanda baiknya keislaman seseorang.”
Segala sesuatu memiliki tanda-tanda, dan hadis ini memaparkan tentang salah satu tanda baiknya keislaman seorang hamba. Hadis ini secara implisit menunjukkan bahwa agama Islam berlevel dan bertingkat-tingkat, substansi dari perkara ini sejatinya dikandung oleh hadis Jibril, yang menginformasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Jibril ‘alaihis salam kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam terkait Islam, Iman dan Ihsan. Ketiga hal tersebut merupakan representasi dari tingkatan-tingkatan dalam agama.
Islam memiliki dua interpretasi, yang pertama; interpretasi umum, maksudnya adalah agama Islam yang mencakup seluruh syariatnya, termasuk juga mencakup iman dan ihsan, adapun interpretasi yang kedua; adalah interpretasi khusus, yaitu ketika istilah Islam ini datang berdampingan dengan istilah iman dan ihsan, maka masing-masing istilah memiliki interpretasi khusus[24].
Islam dalam perspektif interpretasi khusus adalah representasi dari maratibud din (tingkatan-tingkatan agama). Olehnya, yang dimaksud dengan Islam menurut perspektif ini adalah tingkatan dalam Islam yang dominan di dalamnya amalan-amalan lahir, dan tentunya ada sisi amalan batinnya namun kadar dan persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan amalan lahir.
Hal ini dapat dipetik dari jawaban Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan ini, yaitu dengan rukun Islam yang dominan menjelaskan terkait amalan-amalan lahir. Lalu, di mana letak pembahasan tentang amalan bathin? Jawabannya, terletak pada pembahasan tentang syahadat, sebab di antara syarat melafazkan kalimat syahadat, harus terdapat keyakinan pada hati seorang hamba terkait dengan makna yang dikandung kalimat tersebut. Dalam perspektif inilah keimanan dipersyaratkan pula dalam level Islam ini.
Adapun yang dimaksud dengan iman adalah jenjang yang amalan-amalan hati menguat di dalamnya, tentunya pada jenjang ini amalan lahir tetap sangat urgen, sebab level iman berada di atas level Islam, dan amalan lahir merupakan bagian dari keimanan. Namun demikian, yang membedakan level ini dengan level yang sebelumnya adalah kualitas amalan batin atau amalan hati yang menguat.
Jadi pada level islam, amalan lahirnya dominan, sedangkan amalan batinnya mencukupi kadar wajib atau kadar minimal bagi seorang muslim, sedangkan pada level iman, amalan batinnya sudah melebihi level kadar wajib atau kadar minimal, bahkan sampai pada level kadar mustahab (kadar yang lebih tinggi dari kadar wajib atau kadar minimal). Adapun pada tataran amalan lahir, tentunya juga baik, sebab kualitas keimanan mempengaruhi kualitas amalan dan kuantitasnya.
Adapun tingkatan ihsan, maka ini adalah level yang lebih tinggi lagi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendeskripsikannya dengan sabdanya,
أنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاك
“Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak mampu melihat-Nya, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah melihatmu.”[25]
Tingkatan ini bukan hanya mapan dari sisi amalan lahir dan batin semata, namun lebih dari itu yaitu telah sampai pada level muraqabatullah (merasa senantiasa dilihat dan dikontrol oleh Allah azza wa jalla), dan berusaha untuk sampai pada level musyahadatullah (level melihat dan menyaksikan Allah). Yang dimaksud dengan musyahadatullah ini, bukan melihat dan menyaksikan zat Allah secara langsung sebagaimana dipahami oleh sebagian kelompok menyimpang, namun yang dimaksud disini adalah musyahadah sifat-sifat Allah, sebab seorang muslim setiap bertambah ilmunya terkait Allah azza wajalla dan bertambah keyakinannya terhadap sifat-sifat Allah azza wa jalla, akan berimplikasi terhadap keimanannya kepada Allah, dan akan mengembalikan segala yang terjadi di dunia ini kepada sifat-sifat Allah. Tafakkur terhadap nama dan sifat Allah ini akan melahirkan pengagungan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta’ala, sehingga seorang hamba dapat “menyaksikan” kemahabesaran, kekuasaan, pengetahuan Allah azza wa jalla yang Maha Agung dan meliputi seluruh alam semesta. Dari sinilah akan tumbuh al-khasy-yah (rasa takut kepada Allah yang berlandaskan ilmu), sehingga lahir pengagungan yang luar biasa kepada-Nya, bahkan sampai tidak berani menyingkap auratnya kendati ia sedang sendiri, demi mengejawantahkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,
إن الله أحق أن يستحيي منه الناس
“Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk (seorang hamba) malu kepada-Nya.”
Tentunya dua sikap ini (muraqabatullah dan musyahadah) memiliki implikasi yang sangat positif bagi amalan lahir dan batin seorang hamba, bahkan dapat menghantarkan pada kesempurnaan iman.[26]
Pembahasan terkait maratibud din ini diakomodir pula oleh Al-Qur’an, dan secara eksplisit dipaparkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya,
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير
“Kemudian Kami wariskan Kitab itu kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba berbuat kebaikan di izin Allah azza wajalla, yang demikian itu adalah karunia yang besar.” (Surah Fathir: 32)
Kendati istilah yang digunakan dalam ayat ini berbeda, namun substansinya mirip, yaitu terbagi menjadi tiga level, yaitu;
Pertama menzalimi diri sendiri (zalimun linafsihi).
Kedua: pertengahan (muqtashid).
Ketiga: orang yang berlomba-lomba dalam ketaatan (sabiqun bil khairat).
Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan terkait dengan ayat ini, “Allah mengklasifikasikan orang-orang yang beriman menjadi tiga tingkatan”.[27]
Syekh Abdurrahman Nashir al-Sa’di mendeskripsikan istilah-istilah ini dalam kitabnya[28],
- Tingkatan sabiqun muqarrabun, mereka adalah orang yang melaksanakan amalan-amalan yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunah, serta meninggalkan perkara-perkara haram, dan perkara yang makruh, serta menjauhi sifat berlebih-lebihan dalam hal yang mubah (yang dibolehkan).
- Tingkatan muqtasid, orang yang membatasi dirinya dengan mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya wajib dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wajalla.
- Tingkatan zalimun linafsihi: orang-orang yang melaksanakan sebagian amalan yang diwajibkan, namun juga meninggalkan sebagian yang lain, dan juga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wajalla.
Klasifikasi tingkatan-tingkatan di atas, selain berimplikasi kepada kuantitas amalan dan kualitasnya, juga berimplikasi pada disparitas derajat di surga kelak. Simaklah hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ini,
إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ
“Sesungguhnya penghuni surga melihat tempat-tempat (rumah-rumah) yang tinggi di surga, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit”.[29]
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini dengan mengatakan, “Maksudnya adalah penghuni surga berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan derajat keutamaan dan kemuliaan mereka, bahkan penghuni surga yang tertinggi dilihat oleh penghuni surga yang dibawah mereka bagaikan melihat bintang-bintang di langit.”[30]
- Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:
تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ
“Jika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya.”
Makna dari hadis ini adalah bahwa di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba adalah jika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya di dunia dan di akhirat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[31]
Perkara-perkara yang tidak bermanfaat ada beberapa level:
Pertama: perkara yang diharamkan oleh Allah azza wajalla berupa maksiat dan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik perkataan maupun perbuatan.
Maksiat dan perbuatan dosa bukan saja termasuk perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba, bahkan ia termasuk perkara berbahaya yang wajib untuk dihindari. Allah azza wajalla berfirman:
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
“Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia mendapat azab yang menghinakan.” QS. An-Nisa 14.
Kedua: perkara yang makruh dan perkara yang meragukan.
Kendati secara disiplin ilmu fikih, perkara yang makruh dan yang meragukan tidak mewariskan dosa, namun secara suluk (kesempurnaan iman), meninggalkan perkara-perkara tersebut lebih mulia dan lebih utama. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِه
“Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya.”[32]
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib,
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ
“Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu dan (lakukan) perkara yang tidak meragukanmu.”[33]
Imam An-Nawawi memaparkan makna hadis diatas, “Tinggalkan perkara yang engkau ragukan kehalalannya (kebolehannya), dan kerjakan perkara yang engkau tidak ragu akan kehalalannya.”[34]
Sepintas, penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah di atas sangat sepele dan mudah, namun dapat dipastikan bahwa sangat sulit untuk dipraktekkan oleh mayoritas kaum muslimin, sebab yang mampu menerjemahkan hadis di atas secara verbal adalah orang berkualitas ketakwaan dan keimanannya. Oleh karena itu Hassan bin Sinan rahimahullah mengatakan,
مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك
“Tidak ada perkara yang lebih mudah dibandingkan dengan wara’, (yaitu) tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu dan (lakukan) perkara yang tidak meragukanmu.”[35]
Jadi menurut Hassan bin Sinan, hadis di atas merupakan representasi dari sifat wara’, dan yang dimaksud dengan wara’ adalah,
اجتناب الشبهات؛ خوفًا من الوقوع في المحرمات
“Meninggalkan perkara yang syubhat (tidak jelas hukumnya), karena dikhawatirkan terjerembab ke dalam perkara yang di haramkan (oleh syariat)”.[36]
Al-‘Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memaparkan perbedaan antara wara’ dan zuhud, beliau mengatakan, “Dan perbedaan antara zuhud dengan wara’ adalah bahwa zuhud merupakan proses meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, adapun wara’ meninggalkan perkara yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat.”[37]
Menurut kacamata Ibnul Qayyim rahimahullah, hadis diatas merupakan representasi dari zuhud, dan dalam perspektif beliau, zuhud segaris lebih tinggi daripada derajat wara’.
Ketiga: perkara yang mubah.
Perkara yang mubah sangat luas bahkan cukup sulit untuk dibatasi, sebab diantara kaedah yang diakomodir oleh syariat adalah hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, dan biasanya sesuatu yang dikecualikan sangat minim jumlahnya. Di antara contoh perkara yang mubah adalah makan, minum, tidur, rekreasi (rihlah), bergurau, berbicara, dan lain sebagainya.
Sebagian perkara yang mubah adalah merupakan kebutuhan bagi manusia, bahkan kebutuhan primer bagi mereka, jika ditinggalkan dapat menimbulkan dampak negatif, namun bagi orang yang sampai pada level ihsan (level yang tinggi dalam keimanan) mereka memanfaatkan perkara-perkara yang mubah sesuai dengan kebutuhan pokok saja, dan tidak berlebih-lebihan di dalam memanfaatkannya, sebab berlebih-lebihan dalam berinteraksi dengan perkara-perkara yang mubah minimal dapat menyibukkan seseorang dengan perkara yang sia-sia dalam versi syariat dan maksimal dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat.
Contoh sederhana, seseorang yang berlebih-lebihan dalam makan (makan sampai kenyang sekali), biasanya akan menimbulkan dapak negatif seperti malas bergerak atau dikuasai oleh kantuk sehingga dapat mewariskan malas dalam beribadah atau malas mengerjakan hal-hal yang positif bagi kehidupan agama dan akhiratnya. Demikian juga dengan banyak bergurau dan berlebihan di dalamnya, hal tersebut dapat melalaikan hati dan menimbulkan permusuhan dengan sesama, sehingga justru berubah menjadi membahayakan.
Fikih Hadis:
- Ada tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yang biasanya populer dengan istilah maratibu ad-din, adapun perincian klasifikasinya secara umum ada tiga bagian, kendati ada perbedaan istilah dari masing-masing tingkatan, ada yang menggunakan istilah Islam, iman, dan ihsan versi hadis Jibril yang masyhur, adapula istilah dzalimun linafsihi, muqtashid, dan saabiqun bilkhairat versi surat Fathir, adapula istilah ashabu asy-syimal, ashabu al-yamin, al-muqarrabun versi surat Al-Waqi’ah, istilah-istilah ini memiliki substansi yang mirip.
- Iman bertingkat-tingkat, dan kualitas keimanan berpengaruh terhadap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba.
- Hadis ini mengisyaratkan bahwa ucapan dan perbuatan terbagi menjadi tiga:
- Ucapan dan perbuatan yang membuahkan manfaat
- Ucapan dan perbuatan yang membahayakan
- Ucapan dan perbuatan yang tidak membawa manfaat dan juga tidak membahayakan.
- Mafhum al–mukhalafah (kesimpulan terbalik) dari hadis ini, bahwa syariat ini mengajarkan untuk hidup produktif dan menganjurkan untuk memanfaatkan waktu untuk melakukan perbuatan yang membawa manfaat dan maslahat bagi kehidupan dunia dan akhirat,[38] sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُك
“Bersemangatlah atas perkara yang membawa manfaat bagimu.”[39]
Footnote:
[1]. Jami’ Tirmidzi no hadis: 2317.
[2] . Sunan Ibnu Majah no hadis: 3976.
[3] . Shahih Ibnu Hibban no hadis: 229.
[4] . Taqribut Tahdzib hal. 509, cetakan Baitul Afkar Ad-Dauliyah.
[5] . Al-Kasyif (2/136).
[6] . Al-Musnad no hadis: 1737.
[7] . Taqribut Tahdzib hal. 331.
[8] . Riyadhus Shalihin hal. 73.
[9] . Beliau mengatakan dalam kitab Bulughul Maram, dihasankan oleh Tirmidzi, hal. 332.
[10] . Sebagaimana ucapan beliau di Musnad Ahmad (3/259); Hasan dengan jalur-jalur yang lainnya.
[11] . Al-Muwaththa’ (5/1328).
[12] . Jami’ Ma’mar bin Rasyid (20617).
[13] . Diriwayatkan oleh Al-Qudha’i dalam Musnad Syihab (193).
[14] . Sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami’ul Ulum wal Hikam, hal. 256.
[15] . Syarh ‘Ilal Tirmidzi (1/29).
[16] . Tarikh Al-Kabir (4/220).
[17] . Lihat Jami’ At-Tirmidzi setelah hadis nomor: 2318.
[18] . ‘Ilal Ad-Daraquthni, no pertanyaan: 1389.
[19] . Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami’ul Ulum wal Hikam, hal. 256.
[20] . Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, hal. 256.
[21] . Shahih Al-Bukhari (52) dan Shahih Muslim (1599).
[22] . Lihat Fathul Bari (13/247).
[23] . Jamiul ‘Ulum wal Hikam, hal. 257.
[24] . Syarh Arba’in An-Nawawiyah, karya Syekh Saleh Alu Syekh hal. 39-40, dengan perubahan redaksi.
[25] . Shahih Al-Bukhari (50), Shahih Muslim (9).
[26] . Pemaparan ini disarikan dari Jamiul ‘Ulum wal Hikam, dan Syarh Arba’in An-Nawawiyah, karya syekh Shalih Alu Syekh.
[27] Tafsir Ath-Thabary (20/467).
[28] At-Taudhih wal Bayan Lisyajarati Iman, hal. 19.
[29] Shahih Al-Bukhari (6555) dan Shahih Muslim (2830).
[30] Fathul Bari (6/327).
[31] Diringkas dari Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, hal. 257, dan Syarh Arba’in An-Nawawiyah, karya Syekh Shalih Alu Syekh, hal. 181.
[32] Shahih Al-Bukhari (52) dan Shahih Muslim (1599).
[33] Jami’ At-Tirmidzi (2518), Sunan Ad-Darimi (2532), Sunan An-Nasa-i (5711), Shahih Ibnu Hibban (722).
[34] Riyadhus Shalihin, Hal. 62.
[35] Shahih Al-Bukhari, setelah hadis (2051).
[36] At-Ta’rifat, hal. 252.
[37] Al-Fawaid, hal. 181.
[38] . https://saadalkhathlan.com/1387, dengan sedikit tambahan.
[39] . Shahih Muslim (2664).